NU, Radikalisme dan Tantangannya di Era Milenial

Oleh. : Adlan Daie
Wakil Sekretaris PWNU Jawa Barat.
Jakarta, Inako
Telaah mendalam tentang "Radikalisme" secara epistemologis, historis dan sosiologis tidak mudah dan problematis untuk diurai konstruksinya dalam satu tarikan narasi tunggal. Pemaknaan Radikalisme berkelindan dan bertali temali dengan anasir kepentingan yang mengikutinya dan varian varian perspektif sudut pandang tinjauannya. Dalam perspektif Samuel P. Hungtington, guru besar ilmu politik Harvard University dalam bukunya The clash Of Civilizations And The Remaking Of World Order (1996), Radikalisme dapat dipahami sebagai salah satu bentuk "benturan peradaban" (Clash Of Civilizations), sebuah antitesa atau jawaban 'head to head" atas klaim francis fukuyama, ilmuwan politk Hopkins University, dalam bukunya The end of history (1992) bahwa berakhirnya perang dingin dengan kekalahan Uni Sovyet telah menandai akhir sejarah perabadan umat manusia (the end of history) dimana kapitalisme dan liberalisme adalah pemenangnya. Dengan kata lain, dalam konteks tinjauan Samuel P. Hungtinton di atas, Radikalisme adalah bentuk perlawanan ekstrim terhadap dominasi kapitalisme dan liberalisme dalam tatanan politik dunia.
Dalam konteks keIndonesiaan, merujuk pandangan KH. Makruf Amin, Radikalisme mewujud dalam dua bentuk, yaitu :
Pertama, Radikalisme.agama. Kelompok sosial yang memahami agama secara radikal. Radikalisme agama lahir dari pemahaman doktrin dengan mengutip kitab suci (Al quran), misalnya, bahwa Islam adalah "agama yang sempurna mengatur seluruh sistem kehidupan" (Q.S. Al Maidah: 3). Cara pandang para radikalis meletakkan Islam sebaga "sistem" yang mengatur sepenuhnya keseluruhan sistem kehidupan mulai sistem sosial, politik, ekonomi budaya dan lain lain. Inilah sisi menariknya Radikalisme agama sebagai doktrin ideologis menawarkan "obat agama" bagi mereka yang minimalis pemahaman agamanya akan tetapi mengalami kehampaan jiwa akibat "teror" modernisme, kapitalisme dan liberalisme sehingga memantik tingkat kegairahan mereka yang tinggi akan hadirnya formalisme sistem alternatif dengan atribut atribut formal keagamaan.
Dari sini hulu lahirnya sistem politik "khilafah", lahirnya sikap ekslusivisme (tertutup) mereka di ruang publik, menolak segala sistem dan ideologi lain yang dalam pandangan mereka tidak sesuai dengan doktrin Islam versi pemahaman mereka. Dari sini pula hulu menguatnya fenomena "islam politik", komunitas hijabis, festival hijrah, atribut atribut syar'i seperti baju gamis, cadar, celana cingkrang dan lain lain yang sesungguhnya dapat kita pahami sejauh sebagai bentuk out put lahiriyah dari ekspresi keyakinan atas agamanya akan tetapi menjadi problem secara sosial jika dipahami sebagai "paling syar'i" , melabeli pihak lain di luar kelompoknya sebagai "thaghut" dan "kafir".
Ringkasnya, radikalisme agama memahami agama secara tekstualis (harfiah dan rigid) sehingga abai atas substansi _(maqashidus.syari''ah)_ dari pesan agama itu sendiri. Radikalisme agama tidak berkompromi dengan problem problem sosial yang berkembang secara dinamis dari waktu ke waktu (Al umur Al mustajaddah).Mereka menutup diri, menolak.Islam dipahami sebagai sumber nilai dimana prinsip prinsip persamaan hak dan keadilan (Al Masawah wal 'adalah) dapat diinjeksikan dalam varian sistem politik modern yang beragam. Mereka berorientasi keagamaan yang formalistik dan lahiriyah secara ekslusif.
Kedua, Radikalisme sekuler, kebalikan dari radikalisme agama. Yakni kelompok sosial yang memahami agama secara liberal, melampaui batas batas yang ditentukan oleh syara". Menjauhkan nilai nilai agama dan semangat religiusitas (al ruh al diniyah) dalam kehidupan bernegara. Harvey Cox, seorang pakar sekularisme, lebih detail merumuskan tiga pilar sekularisme :
1.Dischanment of nature. Kehidupan dunia harus disterilkan dari pengaruh rohani dan agama. Dalam konteks ini, radikalisme sekuler hakekatnya adalah liberalisme yang membatasi peran agama hanyalah persoalan personal. Agama cukup sampai di dinding masjid atau gereja. Dus, radikalisme sekuler hendak menyingkirkan agama dari ruang kehidupan publik (negara).
2.Desacralization of politics. Dunia politik harus dikosongkan dari pengaruh agama dan nilai nilai spritual. Agama dan segala simbolnya dilarang terlibat dalam urusan politik. Agama satu hal dan politik adalah hal yang lain. Keduanya terpisah, tidak dapat disatukan satu sama lain.
3.Deconsecration of values. Inilah doktrin radikalisme sekuler yang menisbikan kebenaran yang ada dalam kitab suci. Radikalisme sekuler memandang kitab suci bernilai relatif, tidak mutlak. Karena itu, kelompok sosial radikalisme sekuler cenderung mengolok olok kitab suci mereka sendiri, termasuk kitab suci orang lain.
Kedua bentuk radikalisme diatas, baik radikalisme agama.maupun radikalisme sekuler mengalami penguatan intensi di ruang publik, saling meniadakan satu sama lain.Radikalisme agama hendak memono-agamakan, bahkan 'mensyariatkan' Pancasila dalam tafsir tunggal. Sementara radikalisme sekuler hendak mensekularisasikan Pancasila dengan menjauhlan agama dari ruang ruanf publik milik negara. Dua entitas radikalisme diatas secara ideologis baik doktrin nilai instrinsiknya secara laten maupun perwujudan sistem sosialnya secara manifes sangat berbahaya dan nyata nyata bertentangan dengan Pancasila, ideologi negara dan falsafah kehidupan berbangsa kita di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lalu bagaimana NU, ormas Islam terbesar di Indonesia pendukung setia ideologi Pancasila merespons tantangan arus besar dua bentuk radikalisme, baik radikalisme agama maupun radikalisme sekuler diatas? Strategi atau model ijtihad metodologis apa yang dapat direkonstruksi NU di era milenial, sebuah era yang dalam penelitian Boston Consulting Group (BCG) dicirikan era "gampang bosan",No gadget no life, serba cepat, instan dan pragmatis dalam mereposisi responsnya terhadap menguatnya intensi tantangan radikalisme agama dan radikalisme sekuler di ruang publik? Pendekatan moderat NU Al Muhafadloh 'ala al qodimi al shokeh wa al akhdu 'alal al jadid al aslah, memelihara tradisi lama yang baik dan membuka diri secara akomudatif atas inovasi baru yang lebih baik, bagamana seharusnya diletakkan di tengah tarikan keras radikalisme agama di satu pihak dan radikalisme sekuler di pihak lain? Pertanyaan pertanyaan inilah penulis coba deskripsikan dalam lanskap sejarah perjalanan NU dengan segala dinamika sosial politik yang dilewatinya untuk menarik benang merah kekuatan doktrin keagamaan yang dianut NU dan kemampuan adaptasinya terhadap tantangan perubahan masa depan, termasuk tantangan menguatnya intensi radikalisme agama dan radikalisme.sekuler di era milenial ini?
NU sebagai Jami yah diniyah wal ijtimaiyah (Organisasi keagamaan dan sosial kemasyarakatan) lahir pada tanggal 31 januari 1926 M/ 16 Rajab 1344 H. Lahir melalui proses dinamika pemikiran yang panjang para pendirinya, melewati fase fase organik tumbuhnya kesadaran nasionalisme dan resonansi karakteristik pandangan keagamaan sosio masyarakatnya sebagaimana digambarkan secara baik oleh Martin Van Brunessen, seorang antropolog Utrect, Belanda, dosen tamu di.IAIN (kini: UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta (1991-1993) dalam bukunya NU: Tradisi, relasi-relasi kuasa, Pencarian Wacana Baru (1994).
Doktrin keagamaannya dibangun diatas platform Tawashut, tasamuh, tawazun wal i'tidal (moderat, toleran, berimbang dan berkeadilan). Secara Aqidah mengikuti aqidah Al asy ri yah dan Al maturidiyah, faham moderasi dari aliran mu'tazilah (rasionalism) dan aliran jabariyah (ketertundukan non ikhtiary). Di bidang fiqih mengikuti salah satu dari empat madzhab (madzahibul arba'ah) dengan dominasi madhab Syafie, sebuah madhab yang nyaris sempurna memadukan pendekatan tekstual dan kontekstual sebagaimana, antara lain, tercermin dalam kitab teori hukumnya Al Risalah. Dalam konteks tasawuf mengikuti Imam Al junaed Al Baghdadi dan Al ghazali , perpaduan moderat antata aspek eksoteris (lahiriyah) dan aspek.esoteris (batiniyah) agama. Agama tidak kering, tidak berhenti pada batas halal haram, melainkan menembus kedalam suasana kebatinan masyarakatnya seperti.praktek ziarah kubur, tahlil, marhabanan dan lain lain.
Doktrin keagamaan di atas itulah yang membingkai pandangan NU dalam perjalanan kiprahnya dalam dimensi sosial politik kebangsaan dan kenegaraan. Tahun 1936, sembilan tahun sebelum Indonesia merdeka, Muktamar NU ke -11 di Banjarmasin, salah satu keputusannya menunjukkan sisi moderasi NU dengan pendekatan "damai" model ushul.fiqh (legal maxim) yang merupakan basis kekayaan tradisi intelektualnya. NU menerima kehadiran penjajahan belanda dalam merespons konteks sosial politik di masanya, bahwa bagi NU sistem politik dan model kenegaraan hanyalah pilihan relatif, tidak bersifat doktrinal, sejauh kompatibel bagi terwujudnya tertib sosial bersama dan tidak menghalangi kebebasan penduduknya melaksanakan ibadah sesuai agama yang dianutnya.
Transisi perpindahan kekuasaan dari Belanda ke kekusaaan Jepang tahun 1942, dengan janji kemerdekaan Indonesia, disambut dengan baik oleh NU dalam sebuah kompromi pembentukan "shumubu", sebuah kantor jawatan urusan agama, dipimpin KH. Hasyim Asy ary, Rois Akbar sekaligus Pendiri NU dengan pelaksana harian KH Wahid Hasyim, putranya. Kantor jawatan urusan agama inilah yang kelak bertransformasi menjadi departemen/ kememterian agama dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sesuatu yang tidak ditemukan dalam negara sekuler dimana.agama diletakkan sebagai ururan _"fully private"_ , sepenuhnya bersifat pribadi.
Dinamika keterlibatan NU dalam perjuangan kebangsaan dan kenegaraan, antara lain, tercermin pula dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), bentukan jepang, tentang perumusan dasar ideologi negara indonesia merdeka hingga lahirnya rumusan Pancasila tanggal 22 juni 1945 yang dikenal dengan "Piagan Jakarta" dengan sila pertama berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan.syariat Islam bagi pemeluknya". Tanggal 18 agistus 1945, sehari setelah proklamasi kemederkaan, sidang terakhir Pantia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) golongan nasionalis dan golongan Islam mencapai titik komptomi.final tentang rumusan Pancasila dengan merubah sila pertama menjadi "Ketuhanan yang Maha.Esa, membuang kata "dengan kewaiban menjalankan syariat Islam.bagi pemeluknya', sebagaimana rumusan Pancasila yang kita kenal hari ini.
Fatwa Resolusi Jihad NU tanggal 22 oktober 1945, tiga bulan setelah proklamasi Indonesia merdeka, adalah.bentuk jihad fisik NU dalam kerangka memperhatahan nasionalisme Indonesia merdeka dan menolak kehadiran kembali penjajahan Belanda dan sekutunya. Effect fatwa Resolusi jihad inilah yang memantik semangat perjuangan seluruh bangsa Indonesia.Sebuah kontribusi historis NU melengkapi sejarah panjang keterlibatannya merebut dan mempertahanlan eksistensi.negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kelak menjadi inspirasi lahirnya Hari Santri Nasional (HSN) setiap tanggal 22 oktober.
Demikianlah sedikit gambaran sketsa lintasan sejarah.keterlibatan NU dalam perjuangan fisik dan perumusan final dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yakni Pancasila yang dipahami sebagai "kalimatun sawa", titik temu dari kemajemukan anasir anasir bangsa Indonesia. Modal.kematangan historis ini pula.yang menguatkan cara pandang keagamaan NU untuk menjadi pelopor ormas Islam di Indonesia yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal kehidupan berbangsa dan bernegara melalui keputusan Muktamar NU ke-27 di Pesantren salafiyah syafi'iyah. Sukorejo. Situbondo, Jawa Timur.
Power point yang hendak disampaikam.dari deskripsi tentang doktrin keagamaan NU dengan segala lintasan sejarahnya di atas adalah:
Pertama, bagi NU penerimaan final atas kesepakatan empat pilar kenegaraan dan kebangsaan, yakni. Pansasila, UUD 1945, NKRI dan Bhineka Tunggal Ika, bukanlah sekedar pilihan politik akomudatif, kompromistis dan pragmatis sebagaimana digambarkan banyak analis politik tehadap NU, bahkan terkadang "dituduh" opurtunistik dan pada saat yg lain dituduh "radikal" dalam lintasan sejarah perjuangannya tanpa meletakkan konteks "sebab" yang mengikuttinya yang dalam kaidah fiqih NU dikenal _"Al hukmu yaduru ma'al illah"_„ keputusan tergantung konteks "sebabnya".
Doktrin dan cara pandang keagamaan NU yang moderat, toleran, berimbang dan.berkeadilan menjadi titik temu "kedalaman nilai" Islam dengan nilai nilai Pancasila. Pancasila kokoh sebagai asas berbangsa dan bernegara karena ditopang cara pandang keagamaan NU yang dianut mayoritas muslim di Indonesia.
Kedua, cara pandang keagamaan NU yang moderat diatas menjadi arus utama pendekatan "soft approuch", pendekatan lunak yang substansial untuk membendung bahaya penetrasi radikaisme.agama dan radikalisme sekuler di ruang publik yang akhir akhir ini makkn menguat. Radikalisme agama ditarik ke tengah dengan cara pandang keagamaan NU yang moderat secara substansial, tidak bersifat artifisial dan atributif dengan pola framing pejoratif terhadap celana cingkrang cadar dan lain lain karena sumber radikalisme terkait dengan pemahaman keagamaan yang tekstual ekstrim dan ekslusif. Sedangkan aksesoris fashion hanyalah output dari aktualisasi keagamaan seseorang yang tidak selalu berbanding.lurus dengan radikalisme.agama, bahkan justru bagian.dari keragaman budaya yang bhinneka dan dijamin Konstitusi UUD 1945, kecuali bersifat tertutup secara sosial dan menghakini "kafir" terhadap.kelompok lain diluar kelompoknya.
Disisi lain, radikalisme sekuler, sebuah faham liberalis yang menjauhkan simbol simbol agama di ruang publik negara, cenderung mempertentangkan syariat dengan kerangka yuridis perundang undangan negara, seperti usulan menghapus "perda perda" dengan intensi muatan syariat, penghapusan kolom agama dalan KTP, penghalalan LGBT atas nama.HAM dan yang terbaru usulan penghapusan masjid dan mushalla di sekolah sekolah umum milik negara,, harus ditarik ke tengah pula dengan sublimasi cara pandang keagamaan.NU yang moderat, bahwa nilai nilai keislaman bisa berjumpa dalam satu titik temu yang saling menguatkan nilai nilai Pancasila.
Di sinilah peran penting NU dengan doktrin keagamaannya yang moderat. NU menjadi.tali simpul tengah dari tarikan radikalisme agama di satu pihak dan tarikan radikalisme sekuler di pihak lain. Ketidakseimbangan (tawazun) NU dalam memaknai radikalisme, hanya fokus pada ikhtiar membendung arus radikalisme agama dengan membiarkan radikalisme sekuler berkecambah di ruang publik, atau sebaliknya, akan melahirkan sikap perlawanan di antara kedua belah pihak yang sama tingkat bahaya radikalisasinya. Inner power atau kekuatan doktrinal kegamaan NU yang moderat memilikii kapasitas dan kemampuan untuk meletakkan dua model radikalisme diatas dalam satu titik keseimbangan dalam kerangka penguatan nilai nilai Pancasila.
Takdir NU sejak awal berdirinya dan dalam perjalanan sejarahnya yang tidak memiliki "cacat historis" dalam ideologi kebangsaan, dalam konteks era mienial, sebuah era serba cepat, instan, pragmatis dan "no gadget no life", tentu menghadapi tantangan sosial dengan langgam yang berbeda, membutuhkan adaptasi taktis dalam metodologi dakwah dan relasinya dengan negara. NU sebagai ormas Islam harus tetap diletakkan sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil (civil sociaty), bukan ormas perangkat pendukung pemerintah. Strategi "dekat tapi tidak melekat", yakni keseimbangan proporsional antara dukungan dan kritik NU terhadap pemerintah harus tetap berjalan, istiqamah mengikuti prinsip prinsip jam'iyah: tawashut, tasamuh, tawazun dan i'tidal.
Artinya, dukungan NU terhadap pemerintah dalam konteks politik kebangsaan dan kenegaraan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika) dan program program turunannya yang manutun bil maslahah, maslahat bagi kesejahteraan umum, menjaga tertib sosial seperti kampanye anti hoax tanpa alpa mengingatkan pemerintah tentang bahaya membiarkan potensi konflik sosial yang dipicu sikap rasialisme yang antagonistik, tidak absen pembelaannya terhadap ikhtiar pemberantasan korupsi dan pro aktif memperjuangkan tatanan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan sosial.
Di sinilah makna politik dalam perspektif Al Mawardi dalam kitabnya Al ahkam Al sulthaniyah, bahwa Al syiasah li hifd din wa syiasatu Al dunnya, makna fungsional.politik adalah dalam kerangka menjaga "ruh" agama dan semangat religiusitas dalam mengelola kehiduoan dunia (negara) untuk kepentingan maslahat bersama.
Tanggjungjwb NU adalah menjaga titik keseimbangan makna fungsional politik diatas dengan adaptasi metodologi dakwahnya terhadap kecenderungan era milenial dengan pola hidup yang serba cepat dan instan tanpa kehilangan "ruh" pandangan moderasi keagamaannya. Dengan adaptasi taktis dan metodologis itulah kecenderungan semarak keagamaan masyarakat urban di satu pihak dan marginalisasi simbol simbol keagamaan di ruang publik di pihak.lain, dapat dicegah potensinya menjadi manifes radikalisme agama dan radikalisme sekuler. Tanpa adaptasi metodologis dakwah NU yang tepat dan reposisi relasinya dengan negara di.era milenial ini, NU bukan.saja akan kehilangan peran strategisnya dalam memoderasi kehidupan berbangsa dan bernegara, bahkan akan kehilangan generasi milenial sebagai bagian dari rumpun jemaahnya, lebih berpaling mengikuti.trend komunitas keagamaan masyarakat urban yang acapkali tidak tersambung silsilah tradisi keilmuan, kultur dan pandamgan keagamaannya dengan NU.
TAG#Jakarta, #NU, #Radikalisme
216410938

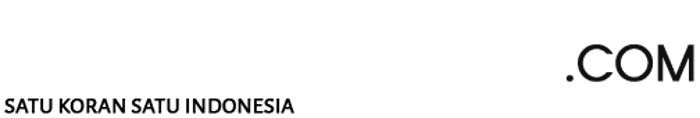
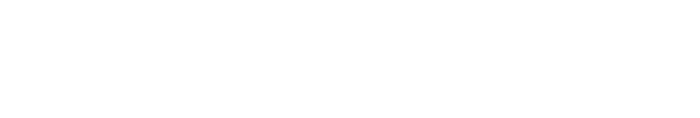











KOMENTAR